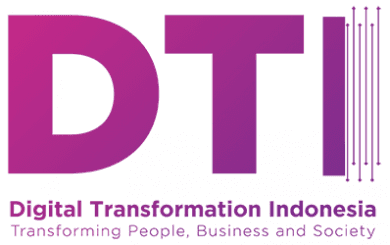Oleh: Arki Rifazka, Kepala Badan Pelaksana Harian, APJII
Pendahuluan: Digitalisasi dan Transformasi Ekonomi
Indonesia sedang menghadapi transformasi digital yang akan menentukan daya saingnya dalam ekonomi global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi pusat ekonomi digital di kawasan. Namun, berbagai tantangan infrastruktur, regulasi, dan kebijakan publik masih menjadi hambatan utama dalam akselerasi perkembangan ini.
Ekonomi digital Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat, sebagaimana dilaporkan oleh Google, Temasek, dan Bain (2024), yang memperkirakan bahwa ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 146 miliar pada 2025. Sektor e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Meskipun demikian, akses internet yang belum merata, regulasi yang masih belum konsisten, serta ketimpangan dalam investasi infrastruktur digital menjadi hambatan yang menghambat inklusi digital secara menyeluruh.
Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia saat ini sedang berupaya bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan)—dua blok ekonomi yang memiliki pendekatan berbeda dalam tata kelola ekonomi digital. Keputusan untuk bergabung dengan salah satu atau kedua entitas ini bukan sekadar persoalan diplomasi, tetapi juga akan berdampak langsung terhadap kebijakan ekonomi digital, regulasi infrastruktur, serta model investasi yang akan diterapkan di dalam negeri.
Digital Public Infrastructure (DPI) dan Relevansinya bagi Ekonomi Digital
Salah satu elemen fundamental dalam pertumbuhan ekonomi digital adalah keberadaan Digital Public Infrastructure (DPI). DPI merujuk pada sistem digital yang mendukung layanan ekonomi dan sosial, termasuk identitas digital, pembayaran elektronik, serta sistem berbagi data yang dapat diakses secara luas dan terstandarisasi.
Beberapa negara telah menunjukkan bagaimana DPI yang kuat dapat mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik serta sektor swasta. India, misalnya, telah sukses mengembangkan Aadhaar, sebuah sistem identitas digital yang kini digunakan untuk berbagai layanan publik dan transaksi keuangan. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan perbankan, bantuan sosial, serta layanan pemerintah dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, India juga memperkenalkan Unified Payments Interface (UPI), yang memungkinkan transaksi digital antarbank secara instan tanpa biaya tambahan, menciptakan revolusi pembayaran digital yang meningkatkan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat.
Menurut laporan OECD (2024), negara-negara yang berhasil mengimplementasikan DPI dengan baik mengalami peningkatan produktivitas hingga lima persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Infrastruktur digital publik yang solid berperan dalam menekan biaya transaksi, meningkatkan transparansi layanan publik, dan mempercepat adopsi teknologi di sektor bisnis.
Namun, Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan DPI. Saat ini, sistem identitas digital yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan berbagai layanan keuangan dan publik. Sementara itu, sistem pembayaran digital masih terfragmentasi dan belum mencapai tingkat interoperabilitas yang optimal. Untuk mengatasi hambatan ini, Indonesia perlu mempercepat pengembangan ekosistem DPI yang kompatibel dengan standar global, namun tetap fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan domestik. Regulasi yang mendukung interoperabilitas antara layanan fintech dan sistem pembayaran nasional perlu segera disusun. Selain itu, pengembangan identitas digital nasional yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi, baik di sektor publik maupun swasta, harus menjadi prioritas.
OECD vs. BRICS: Strategi Digital Indonesia dalam Integrasi Global
Indonesia saat ini berada dalam persimpangan kebijakan digital yang akan menentukan arah masa depan ekonominya. Namun, yang menjadi pertanyaan utama adalah model kebijakan mana yang lebih cocok bagi Indonesia dalam membangun DPI dan ekonomi digitalnya: apakah mengikuti standar OECD yang berbasis pasar terbuka dan persaingan sehat, atau mengadopsi pendekatan BRICS yang lebih protektif terhadap industri dalam negeri? Di satu sisi, OECD menawarkan transparansi regulasi dan keterbukaan pasar yang bertujuan meningkatkan daya saing industri digital. Di sisi lain, BRICS lebih menekankan pada kedaulatan digital, investasi strategis yang dipimpin oleh negara, serta proteksi terhadap industri teknologi dalam negeri.
Sebagai organisasi yang berbasis pada prinsip pasar terbuka, OECD menekankan pentingnya regulasi perlindungan data pribadi yang ketat. Negara-negara anggota OECD umumnya mengadopsi standar General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa, yang mengatur hak pengguna atas data pribadi mereka serta transparansi dalam pemrosesan data oleh perusahaan teknologi. Jika Indonesia ingin bergabung dengan OECD, maka reformasi dalam kebijakan Perlindungan Data Pribadi (PDP) harus dilakukan, termasuk penguatan lembaga regulator data independen serta penerapan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pemrosesan data pengguna.
Selain itu, OECD juga mendorong persaingan yang sehat di sektor telekomunikasi dan teknologi, dengan menekankan pentingnya regulasi spektrum frekuensi yang adil dan transparan. Di banyak negara anggota OECD, pelelangan spektrum dilakukan secara terbuka untuk memastikan bahwa tidak ada pemain dominan yang menghambat inovasi. Bagi Indonesia, transparansi dalam distribusi spektrum menjadi aspek penting yang perlu diperbaiki guna memberikan kepastian bagi investor dan operator telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan infrastruktur mereka.
Di sisi lain, BRICS memiliki pendekatan yang berbeda. Negara-negara BRICS cenderung lebih protektif terhadap industri digital mereka, dengan memberikan peran lebih besar bagi negara dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Investasi infrastruktur yang dipimpin oleh negara menjadi strategi utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi digital. Tiongkok, misalnya, telah melakukan investasi besar-besaran dalam jaringan 5G dan infrastruktur cloud melalui perusahaan-perusahaan milik negara. Rusia dan Brasil juga menerapkan kebijakan serupa, dengan intervensi pemerintah dalam mengarahkan industri teknologi nasional.
Bagi Indonesia, pendekatan BRICS dapat menjadi model yang relevan jika ingin mempertahankan kedaulatan data dan memastikan bahwa industri digital dalam negeri memiliki daya saing yang kuat. Dengan menerapkan kebijakan yang lebih protektif, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan teknologi asing serta mendorong pertumbuhan industri teknologi lokal. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menarik investasi asing yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Implikasi terhadap Investasi Infrastruktur Digital dan Arah Kebijakan Digital Indonesia
Pilihan kebijakan digital yang diambil Indonesia akan berdampak besar pada iklim investasi di sektor telekomunikasi dan infrastruktur digital. Jika Indonesia memilih mengikuti model OECD, maka lingkungan bisnis sektor digital akan lebih terbuka, dengan regulasi yang transparan dan persaingan yang lebih sehat. Hal ini dapat menarik investasi asing ke dalam pengembangan jaringan 5G, pusat data, serta infrastruktur cloud computing. Namun, keterbukaan yang berlebihan juga dapat meningkatkan dominasi perusahaan teknologi asing, yang berpotensi melemahkan industri dalam negeri dalam membangun ekosistem digital nasional.
Sebaliknya, jika Indonesia lebih condong ke model BRICS, maka negara akan berperan lebih besar dalam investasi infrastruktur digital, dengan kontrol yang lebih ketat terhadap sektor strategis seperti pengelolaan data dan jaringan telekomunikasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menjaga kedaulatan digital, namun dapat mengurangi masuknya investasi asing serta membatasi kompetisi yang mendorong inovasi.
Untuk mengatasi dilema ini, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan hibrida yang menyeimbangkan transparansi pasar dan keterbukaan investasi ala OECD dengan strategi proteksi industri yang lebih kuat seperti yang diterapkan negara-negara BRICS. Langkah konkret dalam strategi ini mencakup percepatan pembangunan infrastruktur broadband dan 5G melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP), yang dapat mengurangi beban anggaran negara sekaligus memastikan ekosistem bisnis tetap kompetitif.
Di sisi regulasi, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan data dan spektrum frekuensi mendukung pertumbuhan industri digital nasional tanpa menghambat akses terhadap investasi dan teknologi global. Standar OECD dalam tata kelola data dapat diterapkan untuk memastikan kepercayaan internasional terhadap regulasi digital Indonesia, tetapi kebijakan yang mendukung kedaulatan digital juga tetap harus menjadi bagian dari strategi nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan pusat data nasional dan kebijakan penyimpanan data dalam negeri yang memastikan data pengguna Indonesia tetap berada dalam kendali industri domestik.
Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dengan integrasi ekonomi global. Model kebijakan digital yang seimbang akan memungkinkan Indonesia mempercepat transformasi digital, menarik lebih banyak investasi, serta meningkatkan daya saing industri teknologi dalam negeri. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi asing, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi digital global.
Referensi
- OECD (2024), Digital Public Infrastructure for Digital Governments
- GSMA (2024), Dynamic Spectrum Sharing for 5G Deployment
- Ookla Speedtest Global Index (2025), Internet Speed Ranking
- GSA Spectrum Auction Calendar (Februari 2025)
- IMF (2024), Digital Economy Growth in Emerging Markets