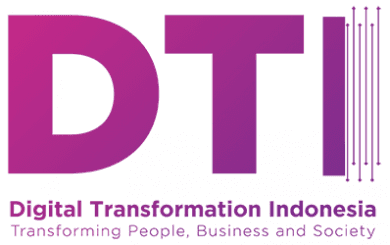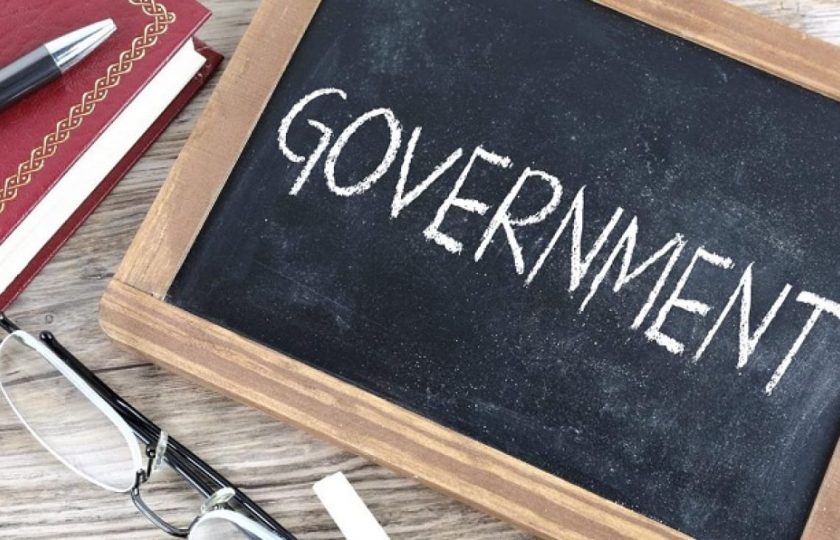Oleh: Arki Rifazka – Kepala Badan Pelaksana Harian, APJII
Indonesia kini menghadapi persimpangan penting dalam kebijakan perdagangan dan industrialisasi digitalnya. Ketika Amerika Serikat meluncurkan skema tarif resiprokal 2025—yang menyasar lebih dari 180 negara—Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan terhadap komoditas ekspornya, tetapi juga potensi gangguan serius terhadap ekosistem teknologi dan manufaktur dalam negeri. Di tengah upaya aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pemerintah Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuan menavigasi ketegangan geopolitik tanpa mengorbankan kepastian regulasi dan daya tarik investasi jangka panjang.
Strategi pemerintah yang disampaikan melalui Rakortas Lintas Kementerian pada April 2025 menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi terhadap tarif AS, melainkan menempuh jalur negosiasi dan stabilisasi pasar. Salah satu opsi yang dikaji adalah relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), terutama untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dinilai AS sebagai hambatan non-tarif. Namun di sinilah dilema strategis muncul: apakah relaksasi TKDN demi kepentingan jangka pendek dapat selaras dengan cita-cita kemandirian industri digital Indonesia?
Dalam konteks daya saing global, langkah relaksasi memang dapat memberikan opsi teknologi yang lebih luas dan murah, terutama untuk produk-produk berbasis Amerika seperti Apple, Oracle, hingga perangkat jaringan. Namun, pelaku industri dalam negeri mengingatkan bahwa dampak jangka panjang dari kebijakan ini bisa sangat merugikan. Pabrik-pabrik komponen seperti fiber optik, perangkat HKT (handphone, komputer, tablet), hingga sistem konektivitas yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade berisiko tergeser oleh produk impor yang masuk tanpa kontrol. Akibatnya, efek domino terhadap ketenagakerjaan dan kepercayaan investor menjadi ancaman nyata.
Di sisi lain, analisis dari Trade War 2.0 yang diterbitkan LPEM FEB UI menunjukkan bahwa dampak kebijakan tarif resiprokal AS bukan sekadar pada barang fisik, tetapi juga menyentuh sektor digital seperti perangkat lunak, lisensi API, dan layanan cloud. Dengan ketergantungan tinggi terhadap sistem operasi dan platform global berbasis AS, sektor digital Indonesia menjadi rentan terhadap pembatasan lisensi atau sanksi non-tarif. Ini menambah kompleksitas bagi startup lokal yang sejak awal sulit bertahan dalam ekosistem digital yang kompetitif dan bergantung pada interoperabilitas global.
Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh pelaku industri internet. Dalam suatu wawancara di Pro3 RRI, disebutkan bahwa membuka impor secara penuh tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri justru akan mematikan insentif investasi jangka panjang. Investor yang telah membangun manufaktur dan rantai pasok lokal akan meragukan stabilitas kebijakan, terutama jika insentif diberikan hanya kepada barang jadi impor, bukan pada bahan baku atau komponen produksi. Pelaku industri menekankan pentingnya pembebasan bea untuk komponen produksi dan penguatan pengawasan terhadap manipulasi angka TKDN.
Dalam kerangka ini, kebijakan perdagangan dan industrialisasi tidak bisa dilihat sebagai dua entitas yang saling bertentangan. Justru sebaliknya, keduanya harus dikelola secara terintegrasi dalam strategi jangka menengah yang menempatkan Indonesia sebagai basis produksi yang andal di Asia Tenggara. Jika pemerintah terlalu cepat membuka kran impor demi meredam ketegangan dagang, maka risiko yang dihadapi adalah hilangnya peluang industrialisasi bernilai tambah dan pelemahan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global.
Sementara itu, dari sisi geopolitik, pendekatan AS yang mendorong re-shoring industri melalui tarif resiprokal mencerminkan arus balik dari globalisasi terbuka ke arah kompetisi teknologi dan proteksionisme terselubung. Dalam narasi ini, negara seperti Indonesia tidak lagi cukup hanya mengandalkan pasar domestik yang besar, tetapi juga harus membuktikan kapasitasnya sebagai mitra produksi yang kompetitif dan stabil secara regulasi. OECD, dalam proses aksesi, akan menilai kemampuan Indonesia menjaga prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan konsistensi kebijakan industri.
Oleh karena itu, solusi kebijakan yang ditawarkan tidak bisa simplistik. Relaksasi TKDN sebaiknya dilakukan secara selektif dan temporer, hanya untuk sub-sektor yang benar-benar belum memiliki basis manufaktur nasional. Sementara itu, sektor yang sudah menunjukkan kemampuan produksi dan ekspor, seperti perangkat TIK dan fiber optik, harus tetap dilindungi melalui kebijakan fiskal dan insentif berbasis performa produksi. Kementerian Perindustrian sebagai pemegang mandat TKDN perlu mengonsolidasikan peta jalan industri digital bersama Komdigi dan Kemenko Perekonomian, agar strategi fiskal dan perdagangan selaras menuju tujuan jangka panjang.
Di tengah lanskap perdagangan internasional yang semakin realis dan berbasis kekuatan, Indonesia tidak bisa bergantung pada goodwill diplomatik semata. Negara-negara kuat, seperti AS, membuat kebijakan berdasarkan logika kepentingan domestik, dan negara berkembang seperti Indonesia harus mampu menyesuaikan dengan cara yang tidak mengorbankan potensi pertumbuhan industrinya sendiri. Menurut catatan akademik dan analisis pasca-Rakortas, narasi liberalisme ekonomi yang gagal diterapkan secara adil di tingkat global justru menuntut Indonesia untuk mengembangkan “strategi resiprositas” berbasis kepentingan nasional.
Momentum penyesuaian kebijakan TKDN dan respons atas tarif resiprokal harus dijadikan sebagai titik masuk untuk membangun ulang strategi industri digital nasional—yang tidak hanya responsif terhadap tekanan global, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan inovasi lokal, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Dengan kebijakan yang cermat, prediktif, dan konsisten, Indonesia dapat memperkuat posisinya tidak hanya di mata mitra dagang utama, tetapi juga di arena geopolitik ekonomi global yang makin kompetitif.
Sumber Referensi:
- Trade War 2.0: Potensi Dampak Perang Dagang dan Implikasi terhadap Indonesia, LPEM FEB UI, April 2025
- Siaran Pers Rakortas Kebijakan Tarif AS, Kemenko Perekonomian, 6 April 2025
- Wawancara Ketua Umum APJII dan Ketua Bidang Perangkat Nasional MASTEL Pro3 RRI (April 2025)
- USTR National Trade Estimate Report, 2025
- Google, Temasek, Bain & Company (2024). e-Conomy SEA Report
Registrasi Dibuka: Hadir Kembali di Event Transformasi Digital Terbesar di Indonesia!
6 -7 August 2025 | Jakarta International Convention Center