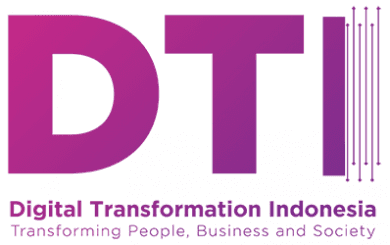Oleh: Arki Rifazka – Kepala Badan Pelaksana Harian, APJII
Indonesia berada di persimpangan penting dalam peta ekonomi digital global. Dalam satu dekade terakhir, negeri ini berhasil membangun fondasi infrastruktur digital yang cukup luas—dari penyebaran jaringan broadband, pertumbuhan pengguna internet aktif yang kini menembus lebih dari 220 juta orang (APJII, 2024), hingga munculnya berbagai startup teknologi dengan valuasi tinggi. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar digital raksasa, atau mampu menjadi produsen nilai dan inovasi digital dunia?
Tantangan terbesar terletak pada lapisan paling dalam dari transformasi digital, yakni kemampuan untuk mengendalikan teknologi inti dan menciptakan produk berdaya saing global. Salah satu indikatornya adalah paten kecerdasan buatan (AI), sebagai proksi dari kapasitas inovasi teknologi nasional. Menurut The 2025 AI Index Report yang dipublikasikan Visual Capitalist, Tiongkok kini memimpin jauh dengan menguasai 70% paten AI global per 2023. Sebaliknya, Amerika Serikat, yang pernah memegang dominasi hingga 40% di tahun 2010, kini hanya menyumbang 14%.
Dominasi paten ini tidak semata-mata simbolik. Di era digital, paten mewakili kendali atas algoritma, model prediktif, dan perangkat lunak yang menjadi tulang punggung layanan modern. Pihak yang mengendalikan paten-paten ini menguasai bukan hanya pasar, tetapi juga standar industri, arsitektur keamanan, dan struktur biaya dalam ekosistem digital. Ketika Tiongkok menutup banyak dari paten tersebut hanya untuk perlindungan domestik, mereka secara strategis memperkuat dominasi tanpa harus bersaing langsung secara terbuka di pasar luar.
Sayangnya, Indonesia belum menunjukkan performa signifikan dalam lanskap paten teknologi. Menurut data WIPO (World Intellectual Property Organization), kontribusi Indonesia terhadap paten teknologi informasi dan komunikasi global masih di bawah 0,1% per tahun. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan mendalam antara ambisi transformasi digital dan kapabilitas intelektual-industri nasional. Pusat data dan konektivitas tetap penting, namun tanpa ekosistem inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual, Indonesia berisiko terjebak sebagai pengguna abadi teknologi impor.
Ke depan, Indonesia perlu merumuskan tiga arah strategis utama untuk memperkecil jurang ini. Pertama, negara perlu membangun ekosistem riset dan inovasi yang berbasis pada research-to-commercialization pipeline. Namun ini lebih mudah diucapkan daripada dijalankan. Hingga kini, banyak hasil riset perguruan tinggi dan lembaga litbang masih berhenti di rak laporan, tidak pernah menyentuh proses inkubasi ataupun tahap komersialisasi. Skema pendanaan riset yang serba birokratis, pendek, dan tidak adaptif terhadap risiko inovasi teknologi menjadi salah satu hambatan utama. Padahal, tanpa sistem insentif yang menghubungkan riset dasar dengan industri, Indonesia hanya akan memproduksi paper, bukan paten. Pemerintah harus berani merombak arsitektur pembiayaan riset—bukan hanya mengganti nomenklatur kementerian—tetapi dengan membuka ruang bagi pendanaan awal (early-stage funding), mempermudah proses paten domestik, serta menjamin perlindungan HKI yang berpihak pada inventor lokal, bukan sekadar memperbanyak konferensi dan MoU simbolik.
Kedua, pemerintah perlu menyediakan insentif fiskal dan perlindungan hukum yang konkret bagi perusahaan teknologi lokal—terutama yang berfokus pada pengembangan teknologi inti seperti machine learning, cloud computing, dan cybersecurity. Sayangnya, kebijakan fiskal selama ini cenderung berpihak pada pelaku besar dan investor asing, dengan janji insentif yang sering kali gagal terealisasi di level implementasi. Tanpa kejelasan aturan turunan dan kepastian insentif jangka panjang, sulit bagi pelaku teknologi lokal untuk bertahan, apalagi bersaing. Bahkan, dalam beberapa kasus, regulasi yang tidak sinkron antara kementerian justru menghambat akses terhadap pasar dalam negeri. Padahal, jika pemerintah serius ingin menumbuhkan talenta digital dan teknologi nasional, maka insentif fiskal bukan lagi soal potongan pajak jangka pendek, tetapi mencakup akses preferensial terhadap proyek pemerintah, pendampingan hukum atas pelanggaran HKI oleh korporasi asing, dan jaminan infrastruktur legal untuk berinovasi.
Ketiga, Indonesia harus memperkuat diplomasi ekonomi digital yang tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam membentuk tatanan digital global. Negara tidak boleh hanya menjadi pengikut pasif dalam forum seperti OECD, WTO, atau APEC Digital Economy Steering Group. Diplomasi digital seharusnya mampu membuka akses pasar luar negeri bagi startup dan teknologi nasional, memperjuangkan akses yang adil terhadap data lintas batas (cross-border data flow), dan menantang dominasi standar teknis yang dibuat sepihak oleh negara-negara maju. Namun, ini menuntut kapasitas negosiator yang paham substansi teknis—bukan hanya gelar diplomatik—dan strategi yang berpihak pada kepentingan jangka panjang, bukan konsesi jangka pendek demi investasi asing. Tanpa perubahan paradigma dalam diplomasi ekonomi digital, Indonesia akan terus menjadi “pasar digital strategis” bagi dunia—tanpa pernah menjadi pemain yang mengatur aturan mainnya.
Perlombaan AI bukan hanya persoalan kebanggaan geopolitik, melainkan ujian terhadap arah pembangunan nasional yang berbasis pada kedaulatan teknologi. Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan negara pengguna dan masuk ke kelas negara pencipta, maka momentum ini harus dijadikan titik balik kebijakan. Tanpa keberanian untuk berinvestasi pada inovasi asli, membenahi sistem paten domestik, dan menghubungkan sektor pendidikan dengan industri teknologi, maka transformasi digital hanya akan menjadi kulit luar tanpa fondasi substansial.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendalam: apakah Indonesia akan menjadi penyewa abadi dalam arsitektur digital global, atau mampu menjadi pemilik dan pencipta algoritma masa depan? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan bentuk ekonomi Indonesia satu dekade ke depan—apakah tetap bergantung pada impor dan konsumsi, atau tumbuh sebagai kekuatan teknologi yang berdaulat dan berdaya saing global.
Registrasi Dibuka: Hadir Kembali di Event Transformasi Digital Terbesar di Indonesia!
6 -7 August 2025 | Jakarta International Convention Center