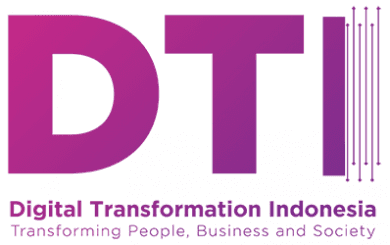Oleh: Arki Rifazka – Kepala Badan Pelaksana Harian, APJII
Peralihan dari SIM fisik ke embedded SIM (eSIM) yang diatur melalui Permenkomdigi No. 7 Tahun 2025 merupakan langkah monumental yang menandai era baru dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi nasional. Di permukaan, kebijakan ini terlihat sebagai respons terhadap kebutuhan teknis dan keamanan digital. Namun jika dicermati lebih dalam, migrasi eSIM sejatinya merupakan peluang strategis yang, bila dikelola dengan cermat, mampu menciptakan efisiensi operasional, membuka sumber pendapatan baru, dan mengonsolidasikan posisi Indonesia dalam ekosistem digital regional.
Secara teknis, eSIM menawarkan berbagai keunggulan. Operator tidak lagi perlu mencetak dan mendistribusikan kartu fisik, yang selama ini menyumbang beban logistik signifikan. Aktivasi dapat dilakukan secara digital, over-the-air (OTA), tanpa kehadiran fisik pelanggan. Ini menciptakan efisiensi biaya di hulu sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang lebih seamless. McKinsey & Company (2022) mencatat bahwa operator di negara-negara maju yang mengadopsi eSIM secara agresif mengalami penurunan biaya operasional hingga 7–10% dalam tiga tahun pertama, khususnya dari sisi manajemen kartu dan proses registrasi.
Namun, implementasi kebijakan ini tentu tidak bebas dari konsekuensi keuangan. Infrastruktur backend untuk provisioning eSIM harus diperbarui, sistem keamanan digital diperkuat, dan kapasitas layanan pelanggan ditingkatkan agar mampu menangani proses transisi secara efisien. Beban awal ini cukup besar, terutama bagi operator dengan populasi pelanggan prabayar yang dominan. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu dirancang secara kolaboratif. Negara idealnya hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, dengan menawarkan keringanan pajak, pengurangan PNBP, dan insentif fiskal untuk transformasi sistem digital yang mendukung eSIM.
Strategi implementasi pun harus disesuaikan dengan segmen pelanggan. Bagi pelanggan pascabayar seperti pengguna Telkomsel Halo, proses migrasi relatif lebih sederhana. Data pelanggan sudah tervalidasi, perangkat umumnya mendukung teknologi eSIM, dan interaksi personal melalui customer service mempermudah transisi. Benchmark global seperti T-Mobile, Vodafone, dan Singtel menunjukkan bahwa migrasi eSIM pada pelanggan pascabayar yang dilakukan melalui notifikasi aplikasi, panggilan proaktif, dan verifikasi digital mampu menjaga loyalitas sekaligus meningkatkan ARPU (average revenue per user).
Sebaliknya, migrasi massal pelanggan prabayar memunculkan tantangan struktural. Banyak pengguna belum memiliki perangkat yang kompatibel, belum terbiasa dengan teknologi eSIM, bahkan tidak memiliki akses email aktif. Risiko seperti kegagalan provisioning, kesalahan input data, kehilangan akses karena lupa sandi, hingga duplikasi NIK menjadi sangat mungkin terjadi. Studi kasus dari India dan Brasil menunjukkan bahwa transisi eSIM pada pelanggan prabayar tanpa edukasi publik dan pendampingan teknis justru memicu lonjakan keluhan pelanggan, backlog layanan, dan churn rate yang tinggi. Karena itu, migrasi prabayar harus diperlakukan sebagai transformasi bertahap, dilengkapi dengan dukungan teknis dari vendor perangkat ponsel dan sistem operasi, edukasi berkelanjutan, dan insentif fiskal yang proporsional dengan beban investasi dan risiko operasional yang ditanggung operator.
Dari sisi ekonomi makro, keberhasilan transisi ini akan berdampak langsung pada struktur industri. Dengan eSIM, operator memiliki keleluasaan merancang model bisnis bundling untuk layanan Internet of Things (IoT), perangkat wearable, hingga integrasi smart city. Ini membuka potensi pertumbuhan pendapatan dari sektor non-tradisional. GSMA Intelligence (2024) mencatat bahwa negara dengan penetrasi eSIM di atas 30% mengalami pertumbuhan pendapatan digital operator 1,5–2 kali lebih cepat dibanding negara yang masih bergantung pada kartu SIM fisik. Dengan kata lain, eSIM bukan sekadar pengganti teknologi lama, tetapi pendorong ekspansi vertikal industri telekomunikasi ke sektor layanan data, cloud, dan monetisasi AI.
Lebih jauh lagi, kebijakan eSIM juga berkaitan erat dengan misi strategis negara dalam perlindungan data, kedaulatan digital, dan efisiensi fiskal. Dengan sistem provisioning yang terpusat dan aman, negara dapat mengatur identitas digital secara lebih presisi. Bila terhubung ke sistem digital ID nasional, maka peluang untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan publik dan memperkuat verifikasi kependudukan digital akan semakin terbuka. Ini menjadi elemen penting dalam menciptakan fondasi digital trust yang kredibel di era ekonomi berbasis data.
Akhirnya, penting untuk diingat bahwa eSIM bukanlah solusi instan bagi seluruh persoalan industri telekomunikasi. Tetapi dalam lanskap yang ditopang oleh regulasi yang progresif, insentif fiskal yang tepat sasaran, serta kesiapan teknologi di level operator dan perangkat, eSIM dapat menjadi fondasi ekonomi digital Indonesia yang lebih efisien, kompetitif, dan resilien. Negara tidak cukup hanya mengatur, ia harus menjadi enabler dan mitra strategis bagi para pelaku industri. Dengan pendekatan inilah, kita bisa memastikan bahwa kebijakan migrasi eSIM bukan sekadar transisi teknologi, melainkan transformasi struktural menuju kemandirian digital nasional.
Registrasi Dibuka: Hadir Kembali di Event Transformasi Digital Terbesar di Indonesia!
6 -7 August 2025 | Jakarta International Convention Center